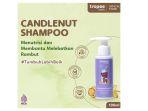Perayaan Imlek 2018
Siapa Sangka, 30 Tahun Dikekang, Imlek Kini Bebas Dirayakan
30 tahun alami pengekangan, imlek kini bebas dirayakan di tanah air. Di zaman orde baru, perayaan ini hanya bisa dilakukan di kalangan terbatas.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Imlek 2018 dirayakan oleh masyarakat di Indonesia, Jumat (15/2/2018) ini . Seperti tahun-tahun sebelumnya warga - umumnya dari suku Tionghoa - bergembira ria merayakan tahun baru China itu.
Kata Imlek (Im=bulan, Lek=penanggalan) berasal dari dialek Hokkian atau Bahasa Mandarinnya Yin Li yang berarti kalender bulan (Lunar Newyear).
Menurut sejarah, Imlek merupakan sebuah perayaan yang dilakukan oleh para petani di China yang biasanya jatuh pada tanggal satu di bulan pertama di awal tahun baru China.
Baca: Tak Hanya Gong Xi Fa Cai, 14 Ucapan Selamat Imlek Ini Juga Bisa Anda Gunakan
Baca: Begini Arti Gong Xi Fa Cai 2018 Sebenarnya, Ternyata Banyak yang Salah Selama Ini
Perayaan ini juga berkaitan erat dengan pesta perayaan datangnya musim semi. Perayaan imlek dimulai pada tanggal 30 bulan ke-12 dan berakhir pada tanggal 15 bulan pertama atau yang lebih dikenal dengan istilah Cap Go Meh.
Imlek adalah tradisi pergantian tahun. Sehingga yang merayakan Imlek ini seluruh etnis Tionghoa apapun agamanya, bahkan menurut Hartati Murdaya, Ketua Walubi, masyarakat Tionghoa Muslim juga merayakan Imlek.
Perayaan Imlek meliputi sembahyang Imlek, sembahyang kepada Sang Pencipta/Thian (Thian=Tuhan dalam Bahasa Mandarin), dan perayaan Cap Go Meh.
Tujuan dari sembahyang Imlek adalah sebagai bentuk pengucapan syukur, doa dan harapan agar di tahun depan mendapat rezeki yang lebih banyak, untuk menjamu leluhur, dan sebagai media silaturahmi dengan keluarga dan kerabat.

Asal-usul Imlek berasal dari Tiongkok. Hari Raya Imlek merupakan istilah umum, kalau dalam bahasa Tiongkok disebut dengan Chung Ciea yang berarti Hari Raya Musim Semi.
Hari Raya ini jatuh pada bulan Februari dan bila di negeri Tiongkok, Korea dan Jepang ditandai dengan sudah mulainya musim semi.
Perayaan Imlek mulai dikenal sejak jaman Dinasti Xia, yang kemudian menyebar ke penjuru dunia, termasuk Indonesia oleh para perantau asal Cina.
Tradisi tahunan itu pun di kenal luas sebagai identitas budaya Tionghoa di tanah perantauan.
Dulunya, Negeri Tiongkok dikenal sebagai negara agraris. Setelah musim dingin berlalu, masyarakat mulai bercocok tanam dan panen. Tibanya masa panen bersamaan waktunya dengan musim semi, cuaca cerah, bunga-bunga mekar dan berkembang.
Lalu musim panen ini dirayakan oleh masyarakat. Kegembiraan itu tergambar jelas dari sikap masyarakat yang saling mengucapkan Gong Xi Fa Cai, kepada keluarga, kerabat, teman dan handai taulan.
Gong Xi Fa Cai artinya ucapan selamat dan semoga banyak rezeki. Adat ini kemudian di bawa oleh masyarakat Tionghoa ke manapun dia merantau, termasuk ke Indonesia.
Perayaan Imlek dari Rezim ke Rezim
Pada era Orde Lama, Imlek tidak bisa terlepas dari dimensi politik. Kala itu, perayaan Imlek diberikan tempat karena Presiden Soekarno membangun persahabatan dengan pemerintah Cina.
Apresiasi pemerintah terhadap Imlek itu dibuktikan dengan kebijakan Soekarno mengeluarkan Ketetapan Pemerintah tentang Hari Raya Umat Beragama Nomor 2/OEM Tahun 1946.
Pada butir Pasal 4 disebutkan, Tahun Baru Imlek, Ceng Beng (berziarah dan membersihkan makam leluhur) dan hari lahir dan wafatnya Khonghucu sebagai hari libur.
Pada masa Orde Baru, etnis Tionghoa mengalami kekangan dari pemerintah. Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.14/1967 tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tiongkok.
Inpres tersebut menetapkan bahwa seluruh upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup.
Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, seluruh perayaan tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa termasuk Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, dan sebagainya dilarang dirayakan secara terbuka.
Termasuk tarian Barongsai dan Liong dilarang dipertunjukkan pada publik.
Inpres ini bertujuan mengeliminasi secara sistematis identitas, kebudayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa.
Kebijakan represif itu diberlakukan lantaran Orde Baru khawatir munculnya kembali benih-benih komunis melalui etnis Tionghoa.
Selain intruksi, ditetapkan pula Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang isinya menganjurkan WNI keturunan yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi.
Kebijakan itu didukung dengan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) yang mengarahkan etnis Tionghoa mau melupakan dan tidak menggunakan lagi nama Tionghoa.
Mereka juga dianjurkan menikah dengan warga pribumi asli, dan menanggalkan bahasa, agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa, dalam kehidupan sehari-hari.
Kebijakan diskriminatif itu yang mengukuhkan sentimen anti Cina dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini berlangsung selama 30 tahun.
Puncaknya, tatkala tragedi Trisakti tahun 1998 terjadi. Kala itu, banyak warga Tionghoa yang eksodus ke luar negeri, dijarah harta bendanya, bahkan tak sedikit perempuan Tionghoa yang diperkosa dan dibunuh.
Berbeda dengan ketika Gus Dur diangkat menjadi presiden ke-4, Gus Dur membuka kebebasan beragama bagi masyarakat Tionghoa dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 pada tanggal 9 April 2001 meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya).
Dengan keppres itu, belenggu terhadap masyarakat Tionghoa pun lepas.
Sejak saat itu hingga sekarang, mereka bebas menggelar perayaan Imlek. Bahkan, kegiatan itu, menjadi hajatan yang juga diapresiasi oleh seluruh lapisan masyrakat Indonesia. (National Geographic)